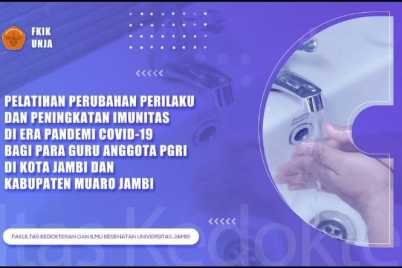Benuanews. Padang, 19/11/2025.-Tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Bahkan tidak henti-hentinya kita melihat berita-berita terkait kekerasan seksual terhadap perempuan yang ada di media sosial dan website berita. Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU), untuk data umum kekerasan terhadap perempuan ada peningkatan jumlah dari tahun 2023 sebanyak 401.975 kasus ke tahun 2024 sebanyak 445.502 kasus. Hal ini tentu menunjukkan peningkatan sebesar 9.77% atau sebanyak 43.257 kasus yang terjadi. Kemudian, Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga 3 Juli 2025, dengan lonjakan lebih dari 2.000 kasus dalam 17 hari, yang mana dalam kekerasan tersebut meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, psikologis, penelantaran dan lainnya.
Jika dilihat dari angka-angka kasus kekerasan terhadap perempuan di atas, ini merupakan hal yang sangat dikhawatirkan dan perlu juga adanya peningkatan kepedulian masyarakat serta pihak penegak hukum dalam menanggapi dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Indonesia. Hal demikian diperlukan, karena perempuan ataupun anak sebagai korban kekerasan seksual seringkali mendapatkan framing dari berita dan juga kekerasan dari oknum kepolisian saat dilakukannya proses pemeriksaan.
Sebagai salah satu contohnya, yakni kasus yang terjadi di Polsek Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya pada awal Maret 2025. Beberapa pemberitaan melaporkan bahwa seorang perempuan korban kekerasan seksual menjadi korban berulang saat melaporkan kasus tindak pidana yang terjadi terhadapnya. Bukannya mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, korban justru mendapatkan pencabulan dari pihak kepolisian saat melakukan pemeriksaan. Bahkan, kasus di atas bukan kasus pertama kalinya, terjadi juga kasus yang sama di awal tahun 2024 di Polsek Tanjung Pandan, Belitung. Dalam kasus tersebut ada seorang anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengurus panti asuhan dengan usia pelaku sudah 53 tahun, kemudian anak tersebut bersama dua temannya melaporkan kekerasan seksual kepada pihak kepolisian, namun bukannya perlindungan yang didapat, justru anak tersebut dicabuli oleh salah satu anggota polisi di sebuah ruangan. Berdasarkan pernyataan jaksa penuntut umum, setelah terjadi pencabulan tersebut korban mengalami Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) komorbid, gangguan campuran kecemasan dan depresif, yang mana ini menjadi dampak psikologis jangka panjang pada kehidupan korban yang masih berusia di bawah umur.
Melihat 2 contoh kasus di atas, pada dasarnya ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), yaitu sebuah lembaga kajian independen dan advokasi yang berfokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum Indonesia sudah menyoroti hal ini juga. ICJR menyoroti bahwasanya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi di Indonesia tidak akuntabel, karena sering terjadinya kasus dimana pihak polisi melakukan penyalahgunaan wewenang, mulai dari penanganan hukum yang berbelit-belit, pemerasan, rekayasa kasus, bahkan maraknya perilaku koruptif yang terjadi di kepolisian.
Selain lemahnya akuntabilitas kepolisian, ICJR juga mencatat bahwasanya KUHAP saat ini belum menjamin adanya pendamping untuk korban terutama korban kekerasan seksual, walaupun memang Indonesia sudah membuat Undang-Undang khusus, yakni UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang mengatur adanya ruang pelayanan khusus di bawah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di lingkungan kepolisian, tetapi tetap saja dalam pengimplementasiannya tidak utuh dan jauh dari yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Pada dasarnya, pemerintah sudah cukup baik berkomitmen dalam membentuk unit PPA di setiap tingkatan kepolisian, namun komitmen ini masih belum sempurna implementasinya, karena sesuai catatan Komnas Perempuan Tahun 2024, baru terbentuk 528 unit PPA di berbagai tingkat kepolisian, yang mana ini masih jauh dari yang diharapkan jika menginginkan perlindungan terhadap korban anak dan perempuan benar-benar terwujud.
Sebelumnya sudah disinggung, bahwasanya kepolisian memiliki Perkap Nomor 3 Tahun 2008 yang bisa menjadi payung hukum bagi para korban dalam hal membuat laporan ataupun mengikuti pemeriksaan. Namun, payung hukum yang seharusnya dirancang untuk melindungi korban terlebih lagi korban kekerasan seksual lebih sering berfungsi sebagai pelindung elegan bagi para pelaku. Dalam retorika hukum, hukum selalu dipenuhi dengan kata-kata perlindungan dan keadilan, namun dalam praktiknya itu sudah berlubang dimana-mana dan membiarkan korban kebasahan oleh trauma, stigma, dan ketidakpedulian.
Padahal sudah jelas diatur di pasal 17 Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Terdapat 4 ayat di dalam pasal tersebut yang menjelaskan betapa peraturan sudah sedemikian rupa dibuat untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi korban, bahkan dari standar urutan pertanyaan pun turut diatur guna terciptanya sikap bersahabat, melindungi, dan mengayomi terhadap korban. Namun, apalagi yang dapat diharapkan dari penegak hukum sekarang, kini polisi sedang berkontribusi dalam siklus kekerasan dan menjalani kurikulum internal, yakni memahami pelaku dengan menjadi pelaku.
Memang sulit untuk dipercaya, tetapi akhir-akhir ini korban kekerasan seksual seringkali mendapat diskriminasi, tidak hanya dari pihak kepolisian bahkan masyarakat juga. Dapat terlihat banyaknya framing yang menyudutkan bahwasanya dalam kekerasan seksual, korban atau perempuan yang patut disalahkan, baik itu dari segi pakaian dan bahkan kesalahan perempuan tersebut semasa hidupnya. Inilah yang seharusnya menjadi evaluasi bagi kita semua, bahwasanya para korban kekerasan seksual tidak seharusnya disudutkan dan dikritik secara berlebihan.
Maka dari itu, perlu sinergitas atau kerja sama yang baik antara unit PPA dan Komnas Perempuan dalam memberikan pemantauan terhadap korban kasus kekerasan seksual yang berurusan dengan kepolisian, pentingnya memberikan penguatan kapasitas penyidik serta dukungan psikososial bagi korban, penguatan kebijakan yang reponsif gender di internal kepolisian, peningkatan jumlah dan keterlibatan polisi wanita dalam menangani korban kekerasan seksual, dan menegakkan kembali peraturan internal kepolisian tentang adanya ruang pelayanan khusus kepada korban kekerasan seksual. Kemudian, masyarakat juga turut andil dalam hal memberikan tanggapan terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi, seperti tidak terlalu menyudutkan pihak korban, ikut membantu korban untuk berani melapor, dan mengutamakan berpikir tentang penyelesaian masalah dibandingkan mencari kesalahan dari pihak korban ataupun pelaku.
Penulis: Fitri Novianti Wulandari
Staff Bidang Pergerakan Kementerian Pergerakan Perempuan BEM KM UNAND Kabinet Pionir Inspiratif 2025